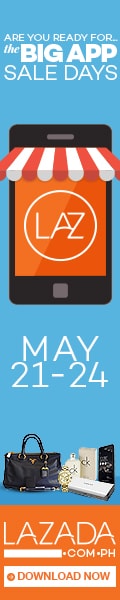Oyisultra.com, KENDARI – Pulau Rempang dan Desa Wadas menjadi simbol krisis agraria nasional yang semakin menguat dalam satu dekade terakhir. Di kedua wilayah ini, negara menggunakan dalih pembangunan dan investasi untuk menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri.
Perampasan tanah atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) memperlihatkan wajah pembangunan yang eksploitatif, di mana masyarakat adat dan petani kecil justru menjadi korban dari model pembangunan yang bertumpu pada akumulasi kapital.
Pola serupa juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Wilayah ini, yang kaya akan sumber daya alam seperti nikel, kawasan hutan, dan lahan subur, mengalami lonjakan konflik agraria akibat ekspansi agresif sektor pertambangan, perkebunan skala besar, dan proyek infrastruktur. Dalam dua dekade terakhir, terutama sepuluh tahun terakhir, konflik agraria meningkat tajam seiring dorongan investasi skala besar yang diberi berbagai kemudahan oleh negara.
Berdasarkan catatan WALHI Sulawesi Tenggara, serta hasil investigasi lapangan, konflik-konflik agraria di Sulawesi Tenggara paling banyak terjadi di Konawe, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Bombana, Konawe Selatan, Muna, dan Konawe Kepulauan. Konflik ini melibatkan masyarakat adat, petani lokal, hingga transmigran yang telah puluhan tahun tinggal dan mengelola tanah secara turun-temurun. Banyak dari mereka kini terancam terusir karena lahan yang mereka kuasai bertumpang tindih dengan izin usaha pertambangan (IUP), hak guna usaha (HGU) perkebunan, atau klaim kawasan hutan.
Permasalahan ini diperparah oleh tidak sinkronnya tata ruang antara pusat dan daerah, lemahnya perlindungan hukum bagi rakyat, serta minimnya akses terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang adil.
Dalam banyak kasus, warga yang mempertahankan tanahnya justru berhadapan dengan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Aparat keamanan kerap dikerahkan untuk mengawal kepentingan korporasi, bahkan ketika rakyat memiliki bukti fisik dan sejarah penguasaan atas tanah tersebut.
Konflik Agraria di Konawe Selatan: Saatnya Penyelesaian yang Adil dan Berani
Kasus di Konawe Selatan menjadi salah satu potret krusial dari krisis agraria di Sulawesi Tenggara. Akar konfliknya bermula sejak era Orde Baru, ketika perusahaan seperti PT Sumber Madu Bukaridan telah di take over berturut-turut ke perusahan PT. Bina Muda Perkasa (BMP) dan ke PT. Marketindo Selaras, masuk ke wilayah tersebut dengan dukungan penuh dari negara.
Saat itu, tidak ada skema inti-plasma seperti yang dikenal sekarang, yang ada hanyalah paksaan kepada masyarakat untuk menyerahkan tanahnya demi proyek perkebunan tebu. Proyek ini dijalankan dengan membentuk Tim 9 oleh pemerintah daerah dan mendapat pengawalan aparat melalui Posko Kewaspadaan Nasional. Dalam praktiknya, negara menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan jalan perusahaan, bukan melindungi rakyat.
Ironisnya, komoditas yang semula dijanjikan sebagai perkebunan tebu kini berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, tanpa persetujuan masyarakat. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana penguasaan tanah dilakukan secara manipulatif, menggunakan narasi pembangunan sebagai kedok perampasan ruang hidup rakyat.
Masyarakat yang sejak awal menolak proyek ini secara tegas menyatakan tidak pernah menyerahkan tanahnya dalam bentuk apa pun. Namun, berbagai tekanan tetap dilakukan untuk melegitimasi penguasaan lahan, termasuk kriminalisasi dan intimidasi terhadap warga yang bertahan.
Gelombang baru konflik muncul ketika PT Merbau Indah Raya Group memperoleh izin lokasi pada tahun 2018. Wilayah-wilayah yang dahulu sudah bermasalah kini kembali dihidupkan sebagai target ekspansi korporasi. Masyarakat kembali mengalami penggusuran berulang-ulang hingga kini, bahkan terhadap lahan-lahan yang telah bersertifikat atas nama mereka. Negara justru memberi karpet merah bagi perusahaan, mulai dari kemudahan izin, pengamanan aparat, hingga skema ganti rugi yang merugikan rakyat.
Padahal, masyarakat tidak pernah meminta ganti rugi karena tidak pernah berniat melepas tanah mereka. Ini adalah bentuk lain dari perampasan tanah secara sistematis yang terus dibiarkan terjadi.
“Pembangunan yang mengorbankan rakyat bukanlah pembangunan sejati, melainkan perampasan. Investasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat dan merusak ruang hidup mereka hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat justru menjadi korban. Seharusnya, pembangunan berfokus pada kesejahteraan bersama, bukan memperkaya mereka yang sudah kuat dengan mengorbankan yang lemah.”
Saatnya Bergerak ke Pendekatan Terpadu
Situasi ini menuntut pendekatan baru yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkeadilan. Kami mendorong agar Pemkab Konawe Selatan segera membentuk Tim Penyelesaian Konflik Agraria Terpadu berbasis skema Reforma Agraria dan pendekatan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria). Tim ini bisa merujuk pada kerangka kerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah dibentuk di tingkat provinsi maupun pusat, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal yang lebih spesifik.
Namun, tim ini tidak sekadar menyalin struktur. Di tingkat kabupaten, peran dan mandatnya perlu diperluas dengan memastikan adanya keterlibatan langsung masyarakat terdampak dalam setiap prosesnya. Mulai dari pemetaan wilayah konflik, membuka ruang dialog yang adil dan transparan dengan masyarakat, hingga verifikasi penguasaan tanah berbasis data lokal yang valid.
Ini tidak hanya soal administrasi, tetapi soal keadilan sosial, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani lokal, serta pemulihan ruang hidup yang telah dirampas.
Proses penyelesaian harus mencakup redistribusi tanah yang adil, serta penataan ulang perizinan yang memastikan tidak ada lagi tumpang tindih antara hak rakyat dan izin usaha korporasi yang tidak memperhatikan kepentingan publik. Lebih dari sekadar menyelesaikan sengketa lahan, ini adalah soal memastikan keadilan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Jalan Penyelesaian yang Adil dan Partisipatif
Langkah Bupati Konawe Selatan harus dilihat sebagai momentum penting dalam memperjuangkan keadilan agraria. Namun, pembentukan tim penyelesaian konflik saja tidak cukup. Prosesnya harus sepenuhnya partisipatif, melibatkan masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga yang memiliki kapasitas dalam pemetaan sosial dan kebijakan agraria.
Selain itu, tim yang dibentuk harus bekerja berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan data dan transparansi yang tinggi. Proses verifikasi penguasaan anah dan dokumentasi harus dapat diakses publik, agar tidak ada lagi ruang bagi manipulasi atau pemalsuan dokumen yang merugikan rakyat. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta memastikan keberpihakan pada pemulihan ruang hidup mereka, harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.
Skema reforma agraria harus dilaksanakan dengan tujuan untuk mengakui, melindungi, dan memperkuat penguasaan tanah oleh rakyat, bukan sebagai sarana legalisasi konflik yang sudah terjadi. Dalam konteks ini, Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, telah memberikan contoh dengan menyatakan, “Kalau sudah jelas dokumen masyarakat sah, jangan digusur. Tapi kalau perusahaan punya dasar hukum yang kuat, silakan lanjut.” Pernyataan tersebut, yang dimuat dalam artikel di media Telisik.id (Telisik.id, 2025), menggarisbawahi pentingnya memastikan kejelasan legalitas baik dari pihak masyarakat maupun perusahaan sebelum melanjutkan penggusuran.
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan tetap netral dalam konflik ini, dengan memastikan proses yang adil dan transparan. “Kami bela masyarakat karena mereka rakyat kami, tapi kami juga dukung investasi. Namun investasi harus paham kondisi masyarakat. Jangan asal gusur tanpa kejelasan administrasi,” lanjutnya, menekankan bahwa pemecahan masalah harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan administrasi yang jelas.
Penutup
Konflik agraria adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja jika tidak diselesaikan secara adil dan menyeluruh. Di Konawe Selatan, masyarakat tidak hanya menunggu, tapi sudah lama menanggung beban ketidakpastian. Pembentukan Tim Penyelesaian Konflik Agraria Terpadu harus menjadi prioritas, bukan hanya sebagai respons administratif, tetapi sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan ruang hidup.
Oleh : Kisran Makati
Direktur Pusat Kajian & Advokasi Hak Asasi Manusia (PUSPAHAM SULTRA).