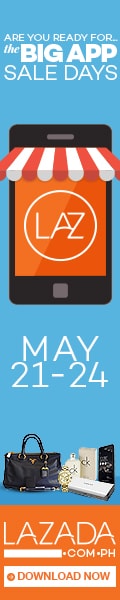Oyisultra.com, MUNA – Fajar menyingsing di balik perbukitan karst jazirah Muna. Kokok ayam bersahutan, hingga mereda seiring merekahnya sinaran di langit. La Ege terbangun, sesaat sadar dari lelapnya tidur pada sebuah Kawale-wale di kebun kecilnya.
Periode memasuki masa panen. Tempo hari beberapa keluarga dari kota datang bersantap jagung bakar. Akhir-akhir ini ia disibukan menjual jagungnya ke pasar. Tak jarang pengepul datang sendiri ke kebunnya. Membeli langsung dan mengangkutnya sendiri untuk di jual ke pasar kota.
Di kebun itu pula ia memelihara ayam kampung. La Ege memberi makan tiap paginya. “Kurrrrr..,” ucapnya dengan nada panjang nan menyaring. Seketika gerombolan ayam berkumpul, tak sabaran menunggu lemparan butiran jagung dari kepalan tangan La Ege.
Kebun kecil itu ia peroleh dari orang tuanya. Proses regenerasi yang hidup dengan bertani ; masyarakat agraris. Jagung memiliki histori yang kuat. Meskipun tak membuat kaya keluarganya. Maklum, pengelolaannya masih tradisional. Tujuannya sebatas mengisi perut dan dijual sekadarnya untuk kebutuhan hidup lainnya.
Tak jauh dari kebun La Ege, terdapat lahan terbuka luas. Dahulu adalah kebun jagung milik La Bore, seluar 5 hektar. Namun dijual ke perusahaan perkebunan sawit. Lumayan murah harganya, sehektar 10 juta. Tak hanya La Bore, beberapa warga lainnya juga tergiur dana segar. Perusahaan mewakilkan seorang warga lokal untuk menjadi juru beli tanah warga. Iming-imingnya menggiurkan.
Seperti La Ege, La Bore juga mendapatkan tanah itu dari orang tuanya. Turun temurun berkebun jagung. Tradisi itu pupus kala La Bore dirayu oleh juru beli tanah perusahan sawit. Angin sorga membius benaknya dalam modus uang dan masa depan penghasilan bulanan.
La Bore tergiur menjadi karyawan di perusahaan perkebunan sawit itu. Setelah menjual lahannya ia konon dipekerjakan sebagai karyawan. Di benaknya ia untung dua kali. Uang kaget jual tanah dan jaminan gaji bulanan sebagai karyawan. Terdengar lebih keren dari sekadar petani tradisional dengan segala peliknya.
Namun, sudah 6 bulan La Bore menunggu pengangkatan karyawan. Hasil penjualan kebunnya perlahan menipis. Konsumsi rumah tangganya naik pasca menjual kebun. Uang kaget mengubah gaya hidupnya. Hasil jual kebun habis buat belanja konsumtif. Beli motor, mesin cuci dan Tv. Celakanya anak-anaknya masih berumur sekolahan, belum ada yang bekerja.
Perusahaan berdalih, bahwa proses pendirian pabrik masih terus diupayakan. Pengangkatan karyawan segera dilakukan. Kebun-kebun yang dibeli sedang diajukan Hak Guna Usahanya (HGU). Berhembus kabar bahwa rencananya HGU itu dijaminkan di Bank dengan nilai yang fantastis. 3 kali lipat dari harga yang dibeli dari warga.
Jika benar kabar itu, perusahaan tentu untung dua kali. Mendapat tanah murah yang luas dari warga, juga meraup dana segar dari Bank. Entah mungkin perusahaan benar-benar membangun pabrik dan menggaji karyawan dengan upah yang layak.
**
Kepemilikan lahan adalah bagian dari hak dasar manusia. Dalam sejarahnya John Locke merumuskannya dalam 3 dasar, yakni hak hidup (life), kebebasan (liberty) dan milik (property). Di bagian hak milik (property) itulah kepemilikan lahan itu berada sebagai hak paling dasar yang dimiliki manusia.
Hak kepemilikan ini mengilhami pemberontakan rakyat Amerika terhadap penguasaan Inggris di tahun 1776. Sekaligus sebagai embrio dalam Declaration of Indepence of The United States atau proklamasinya Amerika. Sebuah sejarah yang kelam, atas perbudakan di tanah sendiri.
Kepemilikan lahan adalah salah satu simbol yang menentukan kelas masyarakat. Apakah ia borjuis ataukah proletar tergantung bahwa dia memiliki lahan dan alat-alat produksi. Proletar terbentuk sebagai masyarakat yang tidak memiliki lahan dan dipekerjakan sebagai buruh dengan sistem upahan. Borjuis adalah pemilik modal yang mempekerjakan proletar.
Di masa kini, perbedaan antara borjuis dan proletar masih dapat ditemukan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri, perdagangan, dan layanan. Masih relevan jika dikaitkan kondisi yang terjadi dalam industri di sekitar kita. Kedua kelas masyarakat ini adalah bentuk kesenjangan yang memiliki potensi konflik.
Karl Marx menyadarkan kita akan bahayanya sistem penghisapan yang kejam namun kasat mata. Sebuah perbudakan dengan modus bekerja di pabrik. Muasal kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? sederhananya adalah meskipun kau bekerja keras siang malam, hidupmu tetap miskin.
Masyarakat yang tidak sadar kadang jadi korban. Melepas lahan dengan harga murah lalu menjadi karyawan dalam skema perbudakan yang dirancang oleh pabrik, yang mengeruk nilai lebih dari segala sisi.
Bisa saja juga ini bagian dari modus penguasaan lahan secara sistematis dan terencana. Modusnya macam-macam. Kita tinggal mengidentifikasi onum-oknum yang sering terlibat, biasanya berasal dari Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), kepala desa, pemborong tanah dan notaris. Orang-orang tersebut biasanya kaya mendadak.
Apakah bekerja di pabrik membuat La Bore kaya? tentu tidak. Hanya membuat ketergantungan bulanan. Bagaimana dengan nasib lahannya? La Bore kehilangan tanah dan aset untuk anak-anaknya yang nilai jualnya meningkat tiap tahunnya, dan tentu saja nilai penjualannya tidak ada apa-apanya dibanding keuntungan yang diperoleh oleh pabrik.
Perusahaan untung berkali lipat. Bayangkan saja, harga tanah 10 juta per hektar digadai jadi 60 juta, lalu kelak ditanami sawit yang dijagai, dipupuk dan dipanen oleh tenaga La Bore sendiri hingga menghasilkan lagi cuan lebih.
Pembelian lahan dari perusahaan adalah pembodohan, cikal bakal perbudakan yang nyata. Notabene masyarakat berhak atas skema bagi hasil, mengorganisasi diri dan memperjuangkan haknya jika memang perusahaan berniat mensejahterakan masyarakat. Tapi faktanya yang terjadi tidak seperti itu.
Pun terjadi skema bagi hasil, perusahaan dan masyarakat pemilik lahan dalam banyak kasus kerap berkonflik. Faktanya, masyarakat seringkali kesulitan mendapatkan haknya karena perbedaan kuasa antara kedua pihak. Perusahaan punya uang, bisa bayar, bayar dan bayar. Sedang masyarakat kerap terkapar oleh pentungan aparat.
Di berbagai daerah di Indonesia, konflik terhadap perusahaan sawit terus terjadi. Ekspansi formal dan informal perusahaan sawit hanya memperkaya oknum tertentu saja dengan pelbagai dampak buruk yang ditinggalkan dari dimensi sosial, ekologi, ketimpangan ekonomi dan budaya.
Dari sisi legalitas, Mahkamah Konstitusi mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Konsekwensinya badan hukum yang melakukan aktivitas budidaya atau pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki IUP dan/atau izin HGU. Kondisi terkini ada 537 perusahaan tidak memiliki izin HGU. Apakah perusahaan pembeli tanah La Bore termaksud? atau bahkan masih mengajukan HGU? Posisi ini bisa saja menjadi momok bagi kepastian keberlanjutan perusahaan.
**
Kembali ke kebun La Ege. Hujan mengguyur dengan derasnya. Terlihat coklatnya air tanah melumer ke areal kebun yang berasal dari lahan terbuka hasil land clearing perkebunan sawit. Sumur gali pun tercemar. Air tadah hujan jadi alternatif.
Kebun-kebun jagung nan hijau terdahulu kini mencokelat. Masyarakat banyak yang tergiur angin sorga perusahaan perkebunan sawit. Rela menukar tanah leluhurnya dengan segepok 10 jutaan saja. Terkecuali La Ege yang teguh berkebun dalam jalan sunyi. Berteman rerimbun jagung dan bersenandung kokok ayam.
La Bore masih menunggu kepastian dari perusahaan. Kapan ia digaji dan berapa gajinya serta apa saja kerjanya. Yang pasti hanyalah bahwa kini dia tak punya lagi kebun. Yang pasti adalah bahwa perusahaan sudah berdaulat di tanah leluhurnya.
Pada akhirnya hidup adalah perjalanan pilihan. Yang mesti dijalani dalam kesadaran dan pengetahuan. Kalau kita tidak sadar, minimal kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu, minimal kita harus sadar. Jangan pernah kehilangan salah satunya, apalagi keduanya.
Menjual tanah bukanlah kejahatan. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekadar keinginan hidup. Tapi, ketika menjual tanah berdampak pada mewariskan kemiskinan, itulah kebodohan jangka panjang, yang tak dapat dimaafkan, pun oleh leluhurmu, yang mati-matian, menyabung nyawa dahulu memperjuangkannya demi generasi selanjutnya. Barakatino Witeno Wuna.
Penulis: La Ode Muhram Naadu (LMN)